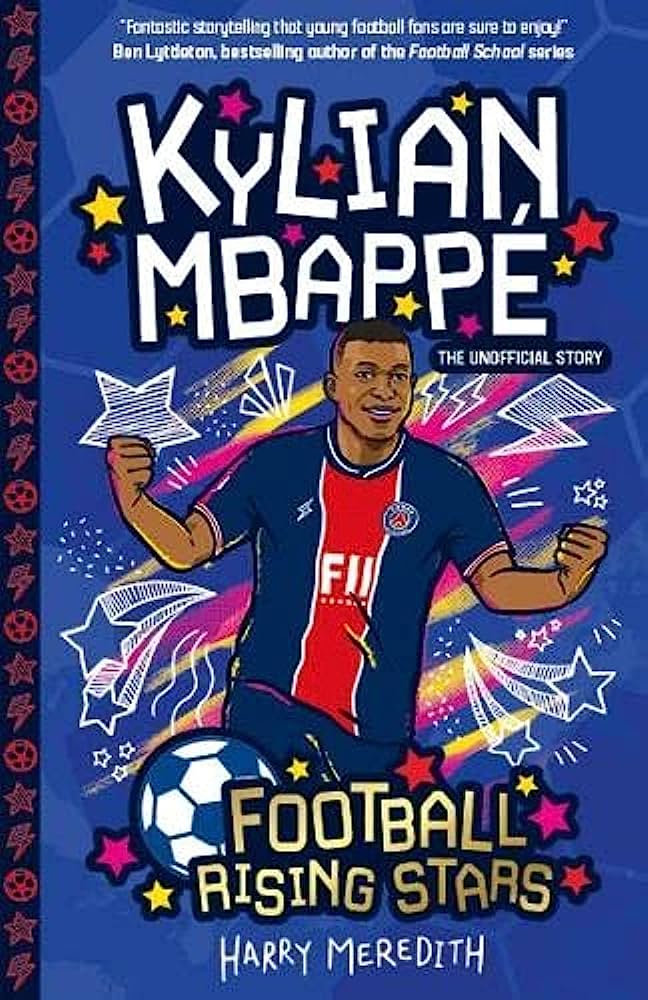TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Tim nasional Prancis gagal ke final Euro 2024 atau Piala Eropa setelah kalah 1-2 dari Spanyol di semifinal di Jerman. Padahal, Prancis, negara yang terletak di benua Eropa, salah satu negara terkuat dan pada masa lalu sangat ekspansif. Banyak negara yang diduduki mereka, setidaknya, ada 24 negara.
Imperium kolonial Prancis adalah imperium yang dominan di dunia dari tahun 1600-an hingga akhir 1960-an, menjajah banyak koloni di berbagai tempat di dunia. Pada akhir abad ke-19 dan ke-20, kekuasaan global Prancis menjadi yang terbesar kedua setelah Imperium Britania Raya. Imperium kolonial Prancis terbentang seluas 24 juta km² pada puncak kekuasaannya.
Dari abad ke-16 hingga abad ke-17, imperium kolonial Prancis Pertama membentang dari luas total pada puncaknya pada tahun 1680 menjadi lebih dari 10 juta km2 (3,9 juta sq mi), imperium terbesar kedua di dunia pada saat itu hanya di belakang Imperium Spanyol.
Selama abad ke-19 dan ke-20, imperium kolonial Prancis adalah imperium kolonial terbesar kedua di dunia setelah Imperium Britania Raya; imperium ini membentang seluas 13.500.000 km2 (5.200.000 sq mi) pada puncaknya pada tahun 1920-an dan 1930-an.
Penggalan dan semangat dari sejarah itu sedikit terlihat di lapangan hijau. Prancis sangat kuat. Begitulah ketika bersiap tampil di Euro 2024 di Jerman. Mereka percaya mampu mengulang sukses di Eropa. Pasalnya, didirikan pada tahun 1904, tim ini memenangkan dua Piala Dunia FIFA , dua Kejuaraan Eropa UEFA , satu Piala Champions CONMEBOL–UEFA , dua Piala Konfederasi FIFA , dan satu gelar Liga Bangsa-Bangsa UEFA (UEFA Nationa League).
Tapi, tak selamanya, keinginan atau tekad berujung dengan kisah seperti Putri Cinderela. “Kompetisi saya? Sulit,” kata Kylian Mbappé kepada wartawan setelah timnya tersingkir. “Itu adalah sebuah kegagalan. Kami punya ambisi untuk menjadi menguasai Eropa. Saya punya ambisi untuk menjadi juara Eropa. Kami tidak seperti itu. Jadi ini sebuah kegagalan,” ujarnya. “Inilah sepak bola.”
Kisah ini mengembalikan cerita kelam Prancis pada 2002 yang berjudul ‘2002: Dari Top of the World ke Bottom of the Barrel’.
Seperti yang dikatakan oleh Deputi Christiane Taubira, seorang anggota terkemuka Majelis Nasional Perancis, “1998 adalah sebuah ilusi dan hanya waktu yang singkat”. Pada tahun 2000, Prancis kembali membuktikan diri sebagai tim elit dunia, kali ini dengan mengalahkan Italia di final Piala Euro. Bahkan banyak yang merasa tim ini lebih unggul, lebih dominan, dibandingkan dengan saat bermain di kandang sendiri pada tahun 1998.
Namun, segalanya segera terungkap, dan hal itu terjadi dengan cukup cepat. Dubois menulis, “Pada akhirnya, kemenangan tahun 2000 lebih terasa seperti gempa susulan tahun 1998 dibandingkan dengan awal era baru”
Maju ke Piala Dunia 2002, dan euforia nasional atas kemenangan Prancis pada tahun 1998 terasa seperti sudah mereda beberapa dekade lalu. Skuad Prancis tahun 2002 terdiri dari delapan pemain berkulit hitam dan sebanyak lima pemain starter, termasuk legenda Prancis Thierry Henry, Claude Makelele dan Lilian Thuram. The New York Times bahkan menyebut orang Prancis yang “berseni” dan “bergaya” sebagai favorit besar untuk mengangkat piala sekali lagi (Clarey). Pemain legendaris Belanda Johan Cruyff mengatakan bahwa “Prancis, di atas segalanya” akan memenangkan Piala Dunia.
Namun, performa skuad mereka sangat buruk, dan kekalahan pembuka yang menakjubkan dan ironis dari Senegal di tengah panggung menyoroti turnamen bagi Prancis. Mereka bangkit dari turnamen di babak penyisihan grup tanpa mencetak satu gol pun. Ini adalah pertama kalinya seorang juara bertahan gagal mencetak gol di Piala Dunia berikutnya, dan pertama kalinya dalam 36 tahun sang juara bertahan gagal lolos dari Babak Grup.
Dan ketika tim nasional Prancis terpuruk di kancah internasional, Ligue 1 Prancis sendiri mengalami episode kekacauan besar. Gelombang kekerasan baru terjadi di berbagai pertandingan di divisi teratas Prancis, tidak hanya antar basis pendukung yang saling bersaing, tetapi juga antar ras yang berbeda, bahkan terkadang dari basis penggemar yang sama.
Bencana ini mencapai puncaknya ketika PSG dan Marseille bersiap untuk bertemu dalam pertandingan sengit mereka pada tahun 2002. Ketua Marseille Pape Diouf menyatakan lapangan kandang PSG “tidak aman” bagi para penggemar Marseille dan menyarankan basis penggemar setianya untuk tidak menghadiri pertandingan tersebut.
Prancis menindaklanjuti kekecewaan di Piala Euro 2002 dengan penampilan buruk lainnya di Piala Euro 2004, saat mereka kalah dari juara mengejutkan Yunani, tim dengan sedikit bakat tetapi semangat dan persahabatan yang besar, di perempat final. Kekecewaan ini segera diikuti oleh beberapa ikon yang pensiun dari sepak bola internasional, termasuk Thuram, Makelele, dan Zidane (yang semuanya kemudian keluar dari masa pensiunnya).
Pengunduran diri ini tentunya menyoroti besarnya gejolak dan ketegangan yang merasuki seluruh tim nasional. Meskipun tim Prancis tampaknya memiliki semua talenta terbaik di dunia, jelas ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mencapai potensi mereka yang sebenarnya.
Kini, bara itu, menjelma menjadi api kembali. Membakar semangat para pemain Les Bleus. Tapi, dinginnya Jerman, memadamkan hasrat dan api yang bergejolak dari dalam diri para pemain Prancis. Kini, seperti 2022, mereka gagal menorehkan tintas emas di EURO 2024.
“Ini tim yang sangat bagus, kami tahu itu, mereka membuktikannya malam ini meski kami mampu membuka skor. Mereka [Spanyol] menciptakan kesulitan bagi kami karena mereka mengendalikan permainan lebih baik dari kami meski kami terus melaju hingga akhir.” Kata pelatih Prancis Didier Deschamps tentang kebangkitan Spanyol untuk mengalahkan timnya dan mencapai final.
Kisah di Jerman ini [Euro 2024] ini seperti mengulang pernyataan terkenal L’Equipe. “Kami [sepak bola Prancis] telah mencapai titik terbawah, ujung jalan”. Seluruh Prancis marah, dan surat kabar nasional seperti L’Equipe dan Le Figaro mulai memperhatikan korelasi mengejutkan antara kekerasan dalam pertandingan sepak bola Perancis dan kurangnya keberhasilan tim nasional Prancis.